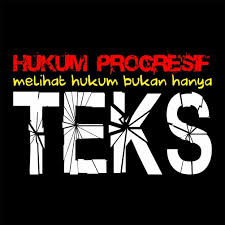Keadilan merupakan hal yang didambakan dalam kehidupan, terlebih bagi para pihak yang sedang berseteru di persidangan. Hukum pada dasarnya bertujuan untuk menjaga dan menciptakan keadilan, akan tetapi tidak jarang keadilan hanyalah sebatas angan-angan yang tak kunjung terealisasikan terutama bagi kaum yang lemah tidak berdaya dan tidak punya wewenang kekuasaan. Bahkan terkadang hukum justru hanya menjadi “komoditas perdagangan” bagi oknum-oknum tertentu yang hanya berorientasi pada kepuasan nafsu keduniawian. Bagi yang “lurus ke depan” dan tahan dengan godaan serta benar-benar murni menegakkan keadilan terkadang terkendala pada kaku dan tekstualnya peraturan perundang-undangan, sehingga putusan yang dijatuhkan kurang memberikan rasa keadilan dan pengayoman. Para penegak hukum perlu mengintegrasikan aspek spriritualisme ke dalam proses persidangan agar hukum yang dihasilkan tidak mengalami ketimpangan dan keambiguitasan. Sebagaimana diketahui bahwasanya hukum tidak hanya terbatas pada pasal-pasal undang-undang yang kaku tekstual dan formal, akan tetapi perlu digali lebih dalam agar ditemukan keadilan yang benar-benar memberikan rasa pengayoman bagi masyarakat, maka berhukum perlu dilakukan secara progresif agar diperoleh keadilan yang substantif. Keadilan substantif merupakan keadilan yang terkait dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak (imparsiality), tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani atau keyakinan hakim.

Secara prinsip, hukum dapat diklasifikasikan ke dalam dua (2) pengertian, pertama yaitu hukum bermakna obyektif, kedua hukum bermakna subyektif. Hukum yang bermakna obyektif mengandung pengertian sebagai peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara sesama masyarakat. Sedangkan hukum yang bermakna subyektif mengandung arti sebagai kewenangan atau hak yang diperoleh seseorang berdasarkan hukum obyektif. Progresif merupakan kata yang bermakna maju, berhasrat maju dan selalu maju. Dari dua makna atau istilah tersebut dapat diambil pengertian bahwa Hukum Progresif merupakan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara sesama masyarakat yang dibuat oleh seseorang atau kelompok yang mempunyai kewenangan membuat hukum dengan landasan keinginan untuk terus maju.
Jika merujuk pada penggagas Hukum Progresif, Prof. Satjipto Rahardjo memaknai bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Hukum tidak ada untuk dirinya melainkan untuk sesuatu yang luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Beliau juga menambahkan bahwasannya hukum bukan merupakan institusi mutlak dan final karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (law as a procces, law in making). Seorang hakim bukan hanya sebagai “teknisi atau corong” pelaksana undang-undang semata, akan tetapi juga sebagai makhluk sosial. Tugas hakim sangat mulia, karena bukan hanya bermain dengan pikiran tapi juga nuraninya, sehingga keberadaan Hukum Progresif bertolak dari dua komponen basis dalam hukum, yaitu peraturan dan perilaku (rules and behavior). Hukum selain ditempatkan sebagai aspek perilaku, juga sekaligus sebagai peraturan. Peraturan akan membangun suatu sistem hukum positif, sedangkan perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah dan akan terbangun.
Hukum Progresif mempunyai keinginan agar kembali kepada pemikiran hukum pada falsafah dasarnya yaitu hukum untuk manusia. Manusia menjadi penentu dan titik orientasi dari keberadaan hukum. Karena itu, hukum tidak boleh menjadi institusi yang lepas dari kepentingan pengabdian untuk mensejahterakan manusia. Para penegak hukum dituntut untuk mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan yang dialami oleh rakyat dan bangsanya. Kepentingan rakyat baik kesejahteran dan kebahagiannya harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari penyelenggaraan hukum.
Hukum Progresif lahir akibat dari carut-marutnya dunia hukum di negeri ini. Hukum Progresif seakan memberitahukan mengenai kesalahan mendasar dalam berhukum selama ini. Menjalankan hukum seyogyanya tidak hanya sekedar tekstual menelan apa adanya dari peraturan perundang-undangan, akan tetapi harus berdasarkan semangat dan menggali makna yang lebih dalam dari undang-undang itu sendiri. Hukum tidak cukup dijalankan dengan kecerdasan intelektual saja, akan tetapi juga harus disertai dengan kecerdasan spiritual.
Hukum Progresif lahir dari keprihatinan terhadap dunia hukum di Indonesia. Gagasan ini berawal dari setting Indonesia pada akhir abad 20 sebagai bentuk dari rasa ketidakpuasan terhadap kinerja penegakan hukum. Sebagaimana telah diketahui bahwa kepercayaan terhadap hukum semakin menurun yang disebabkan oleh buruknya kinerja hukum itu sendiri. Misalkan sejak tahun 70-an, istilah “mafia pengadilan” sudah memperkaya kosa-kata bahasa Indonesia, di mana pada masa itu hukum semakin bergeser menjadi alat politik untuk mempertahankan kekuasaan. Maka akibatnya bukan lagi “law as a tool of social engineering” yang secara positif terjadi, melainkan sudah mengarah kepada “dark engineering”. Pada masa Reformasi sejak tumbangnya Orde Baru pada tahun 1998, bangsa Indonesia juga belum berhasil membawa hukum sampai kepada taraf mendekati keadaan ideal, akan tetapi justru semakin menimbulkan kekecewaan, khususnya berkaitan dengan pemberantasan korupsi, di mana Komersialisasi dan commodification hukum semakin tahun semakin marak terjadi.
Hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya, karena hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Dalam Hukum Progresif, hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, akan tetapi untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Maka Hukum Progresif meninggalkan tradisi analytical jurisprudence atau rechtdogmatick. Hukum Progresif berbagi faham dengan legal realism dan freirechtslehre karena hukum tidak dilihat dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. Karena kehadiran hukum dikaitkan dengan tujuan sosialnya, maka kehadiran Hukum Progresif juga dekat dengan sociological jurisprudence, teori dari Roscoe Pound, di mana Roscoe Pound menolak studi hukum sebagai studi tentang peraturan – peraturan, melainkan keluar dari situ dan melihat efek hukum serta bekerjanya hukum. Hukum Progresif merupakan koreksi terhadap kelemahan sistem hukum modern yang sarat dengan birokrasi dan prosedur, sehingga sangat berpotensi terpinggirkannya kebenaran dan keadilan. Hukum Progresif memasukkan perilaku sebagai unsur penting dalam hukum dan lebih khusus lagi dalam penegakan hukum.
Hukum Progressif mengandung spirit pembebasan, yaitu pembebasan terhadap tipe, cara berpikir, asas, dan teori yang selama ini dipakai, serta pembebasan terhadap kultur penegak hukum (administration of Justice) yang selama ini berkuasa dan dirasa menghambat usaha hukum untuk menyelesaikan persoalan. Spirit tersebut mengindikasikan akan pentingnya rule breaking dalam sistem hukum. Dengan spirit tersebut hakim diharapkan berani melakukan Ijtihad atau keluar dari pola-pola baku yang telah dilakukan. Menurut Sang Maestro Hukum Progresif, Prof. Satjipto Rahardjo dan juga Prof. Suteki, rule breaking dapat ditempuh dengan 3 (tiga) cara yaitu: pertama, Mempergunakan kecerdasan spiritual untuk bangun dari keterpurukan hukum, memberikan pesan penting bagi kita untuk berani mencari jalan baru (rule breaking) dan tidak membiarkan diri terkekang cara lama, menjalankan hukum yang lama dan tradisional yang jelas-jelas lebih banyak melukai rasa keadilan. Kedua, Pencarian makna lebih dalam hendaknya menjadi ukuran baru dalam menjalankan hukum dan bernegara hukum. Masing-masing pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum didorong untuk selalu bertanya kepada hati nurani tentang makna hukum yang lebih dalam. Ketiga, Hukum hendaknya dijalankan tidak menurut prinsip logika saja, tetapi dengan perasaan, kepedulian dan keterlibatan (compassion) kepada kelompok yang lemah. Pencarian keadilan tidak mungkin hanya bisa dilihat dari aspek normatif saja, melainkan juga aspek sosiologis, apalagi sudah menyangkut aspek keadilan sosial (sosial justice) serta konstitusionalitas suatu undang-undang.
Hukum Progressif juga memiliki karakter yaitu bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dan oleh karenanya memandang hukum selalu dalam proses menjadi (law in the making). Hukum Progresif juga peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, baik lokal, nasional maupun global. Hukum Progresif menolak status quo manakala menimbulkan dekadensi suasana korup dan sangat merugikan kepentingan rakyat, sehingga menimbulkan perlawanan dan pemberontakan yang berujung pada penafsiran progresif terhadap hukum. Untuk mewujudkan karakter tersebut, Hukum Progressif harus memiliki sistem hukum yang melampaui segitiga formalism (bentuk, materi, dan proses) yang kemudian dibingkai dengan hermeneutika (perspektif makna). Urgensi penggunaan hermeneutika agar terhindar dari terjebak dan kebuntuan dalam mencari kebenaran dan keadilan substansial. Ketika penegakan hukum masih sebatas pada aspek formal, maka keadilan dan kebenaran substansial yang didambakan para pencari kebenaran dan keadilan tidak akan terwujud, melainkan hanya keadilan prosedural saja yang terwujud. Hal ini terjadi karena para penegak hukum hanya menggunakan pasal-pasal undang-undang sebagai senjata dalam menyelesaikan persoalan hukum tanpa mengetahui ruh dan esensi yang terkandung di dalamnya.
Keadilan substantif merupakan cita-cita masyarakat sekaligus menjadi ruh dalam hukum itu sendiri yang dalam proses mewujudkannya seringkali terkendala pada tekstual formal dan kakunya peraturan perundang-undangan. Proses penegakan hukum perlu pengintegrasian nilai spiritualisme agar keadilan yang memberikan rasa pengayoman dapat terealisasikan. Mekanisme yang dapat dilakukan adalah dengan berhukum secara progresif. Berhukum secara progresif bukan berarti menafikan peraturan perundang-undangan yang ada, akan tetapi memahami ruh, esensi dan substansi dari peraturan yang ada dengan tidak serta merta tekstual dan kaku dalam berhukum. Kemampuan “ijtihad” seorang hakim atau penegak hukum dalam penegakan hukum dengan memperhatikan nilai, norma, sosial dan hal lain yang berkembang di masyarakat menjadi suatu hal yang harus dioptimalkan. Pengimplementasian nilai spiritualisme berupa sikap progresif dalam berhukum menjadi kunci untuk mewujudkan keadilan yang substantif.
Referensi:
Daliyo, dkk. 1996. Pengantar Ilmu Hukum : Buku Panduan Mahasiswa. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Rahardjo, Satjipto 15 Juli 2002. Indonesia Inginkan Penegakan Hukum Progresif, Kompas.
Rahardjo, Satjipto. 2006. Membedah Hukum Progresif. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Rahardjo, Satjipto. 2009. Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta : Genta Publishing.
Rahardjo. Rahardjo. 2005. Hukum Progresif yang Membebaskan. PDIH UNDIP : Jurnal Hukum Progresif, Vol.1/No.1/April 2005.
Suteki. 2010. Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum (Non Enforcement of Law) Demi Kemuliaan Keadilan Substantif. (Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Undip tanggal 4 Agustus 2010).
Yasyin, Sulchan (Ed). 1995. Kamus Pintar Bahasa Indonesia. Surabaya: Penerbit Amanah.
![]()